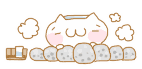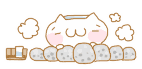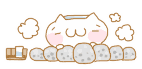A Story: Alone
WRITTEN BY -PM- ON Friday, December 03, 2010 {
4 comments }
Original by me. :) Happy Reading~
SORRY. Indonesia Only
Aku berjalan melewati lorong-lorong gelap. Memang hanya gelap tak berujung yang dapat kulihat. Seingatku, aku tidak dapat ‘melihat’ saat itu. Melihat dengan jelas karena aku terlalu sibuk dengan perasaanku sendiri. Namun kini aku dapat melihatnya. Tersenyum ke arahku. Dan memanggilku dengan suaranya yang merdu.
-Й-
“Ma, aku berangkat dulu ya!” seruku nyaring sambil menutup pintu perlahan.
“Ya, sayang. Hati-hati di jalan,” jawab Mama dari dapur.
Aku berjalan santai melewati jalanan yang sepi. Pukul 6 pagi. Memang jarak rumahku ke sekolah dekat sekali. Cukup dengan sepuluh menit berjalan. Dan berjalan adalah hobiku. Apalagi dengan memandangi matahari yang tersenyum manis dari ufuk timur itu. Membentuk lukisan alam yang indah dipadu dengan langit biru dan beberapa kapas putih awan yang melayang tinggi nun jauh di sana.
Hobiku yang lainnya mungkin adalah menyanyi. Bukan nyanyian yang se-sungguhnya melainkan senandung dalam hati. Aku tidak peduli dengan suaraku yang terlalu nyaring dan tidak cocok untuk menyanyi karena aku hanya menyanyi untuk diriku sendiri. Menyanyi dalam hati. Tentu saja.
Bukan tanpa alasan aku bersenandung riang pagi ini. Bukan senandung dalam hati itu. Senandung yang lain. Senandung berupa nyanyian yang menurutku merdu dengan siulan burung dari dahan-dahan pohon yang rindang. Hanya karena satu hal yang menurutku penting. Aku akan menemuinya. Apapun yang terjadi. Menemui kakak senior itu. Kak Noah.
Dengan satu tarikan nafas, Aku berjalan melewati pintu pagar sekolahku. SMAN 1 Genteng. Cukup mudah untuk berjalan melewati pagar sekolah hingga ke kelas bagi pelajar golongan 'bukan anak populer' sepertiku. Semua tidak mengenalku. Mungkin karena aku selalu sendiri. Dan aku selalu tidak terlihat.
Kesendirian itulah yang kadang menyiksaku. Aku tidak punya teman. Tapi mungkin, Rie satu-satunya temanku. Ia duduk sebangku denganku. Bahkan sejak SMP kami selalu duduk sebangku. Rie jugalah satu-satunya orang yang mau mendengarku bercerita tentang semuanya. Kecuali tentang satu hal. Ia tidak tahu kalau aku menyukai Kak Noah. Dan seperti biasa, ia selalu datang lima menit sebelum bel masuk berbunyi.
“Hah.. hah.. sial..! Nyaris nih pintu gerbang ditutup! Hah... Untung aku kuat lari lagi. Hahaha. Hah.. hah.. Mao ! Hampir aja namaku tercantum di BK!” ujar Rie di sela nafasnya yang terputus-putus.
“Ampun dah. Besok pake alarm yang besar aja, sekalian seperti miliknya Spongebob! Hehe, ” jawabku asal.
“Jah, enggak bakal ada Em !” protes Rie sambil meletakkan tas dan duduk di bangkunya. Ah ya. Rie selalu memanggilku dengan sebutan ini.
“Huh, iya deh,” jawabku tak acuh.
Bel masuk pun berbunyi.
Pelajaran berlalu seperti biasa. Mencatat. Menjawab pertanyaan guru. Maju mengerjakan soal latihan di papan tulis dan ulangan. Aku dengan gembira yang berlebihan segera melonjak dari tempat duduk saat bel istirahat pertama berdering. Akupun bergegas menuju perpustakaan. Tak lupa kubawa juga novel Maryamah Karpov karya Andrea Hirata yang tebal dan penting itu. Bukan novelnya yang penting, tetapi sepucuk surat yang terselip di dalamnya. Dan semalam, aku melihat daftar peminjam terakhir novel itu. Kak Noah.
Sesampainya di perpustakaan, aku meminjam buku daftar anggota perpustakaan dari Bu Siti. Untungnya, beliau dengan senang hati meminjamkannya padaku. Lekas kucari nama Kak Noah. Kak Noah. Oh tidak. Aku bahkan tidak tahu nama lengkapnya. Noah Adisaputra/XI A2/1556, bukan. Yang kutahu, Kak Noah sekarang sudah kelas dua belas. Kucari lagi daftar nama ‘Noah’. Noah Aldebaran/XII A7/1331, yup ketemu.
Aku tidak tahu kelas Kak Noah. Namun, kini aku tahu. Akupun kembali ke kelas dan duduk membaca Maryamah Karpov itu lagi sambil menunggu bel masuk berbunyi. Kurasakan kupu-kupu mengepakkan sayapnya dan menggelitik perutku menciptakan perasaan aneh. Aku bahkan menyukai perasaan ini.
Aku memang penasaran dengan sepucuk surat yang kuanggap milik Kak Noah ini. Bagaimanapun juga, aku berniat membukanya. Toh pikiranku tidak bisa konsentrasi membaca selembar Maryamah Karpov karena setelah itu, aku membaca surat Kak Noah.
Untuk Rie Rahma,
Rie, seperti itukah aku harus memangggilmu? Boleh kan aku memanggilmu dengan sebutan Rahma? Boleh kan? Jawab iya dan mengangguklah. Ah, iya. Aku tidak bisa melihatmu mengangguk. Haha.. Aku ini aneh ya?
Rahma, kau ingat saat MOS dulu? Aku selalu memandangmu. Aku bahkan berfikir untuk mendekatimu tapi aku takut. Aku takut kau akan pergi. Jadi lewat surat ini, aku ingin mengatakan kalau aku menyayangimu apa adanya.
Noah Aldebaran.
Deg! Jadi saat MOS dulu bukan aku yang dilihat Kak Noah. Tapi Rie! Rie yang duduk di sampingku. Rie yang selalu ada di sampingku saat kami makan bersama di kantin atau membaca buku di perpustakaan. Hatiku pecah berkeping-keping. Bagaimana aku bisa menggambarkannya? Seperti perkakas yang jatuh berdentuman di toko kelontong Sinar Harapan saat Ikal patah hati di Laskar Pelangi. Ya, seperti itu. Sungguh menyakitkan. Andai jantungku berhenti ber-detak mungkin sakitnya takkan separah ini.
Jadi seperti inilah sakit hati. Sungguh sepadan dengan jatuh cinta yang melambung tinggi. Sakit hati malah membawaku seperti terjatuh dalam jurang yang dalam tak terkira. Dalam. Dalam sekali. Bahkan seperti ada yang menusuk di dada dan menekan paru-paru hingga sesak. Ingin ku merasakan sakit gigi saja. Setidaknya gigi yang sakit masih dapat diobati. Tapi hati ? Takkan pernah ada obatnya.
Aku yang terlalu bodoh. Aku yang terlalu percaya diri. Aku sungguh malu pada diriku sendiri. Memangnya aku ini siapa? Aku hanya seorang Mao Maura yang tidak punya apa-apa. Aku hanya seorang cewek yang berkulit hitam terbakar matahari yang bahkan sangat kubenci.
Aku benci diriku sendiri. Aku hanya seorang cewek dengan tinggi normal yang tidak dapat menjadi lebih tinggi. Kenapa? Aku ini cewek Asia yang sudah pasti pendek sebagai ciri khas Indonesia daerah pedesaan khususnya. Kekurangan kalsium tingkat tinggi.
Untuk itu aku seringkali ingin merasa egois. Aku ingin dicintai. Tapi oleh siapa? Sampai saat ini, aku bahkan belum pernah punya pacar. Sungguh.
Akupun menutup surat Kak Noah dan memasukkannya kembali ke amplopnya dengan gemetar. Beranikah aku menemuinya setelah aku mengetahui semua ini? Kuharap tidak. Tapi hati kecilku berkata lain. Aku akan tetap menemuinya. Apapun yang terjadi. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri.
Bel masuk pun berdering.
Pelajaran dimulai lagi. Fisika. Rumus GMB. Gerak Melingkar Beraturan. Omega sama dengan dua phi kali frekuensi. Bla.. bla.. bla. Aku benar menyimak Pak Sulton menerangkan tetapi pikiranku melayang jauh hingga kemana-mana. Aku sama sekali tidak bisa berkonsentrasi.
“Em!” panggil Rie samar-samar. Aku tidak begitu mendengarkannya.
“Mao! Sst...!” panggil Rie lagi. Masih dengan berbisik.
“Hm? Apa?” jawabku malas lalu menoleh ke arahnya.
“Kamu sakit ya?” tanya Rie.
“Nggak. Aku nggak apa-apa kok,” jawabku bohong. Orang sakit yang mengaku sakit untuk masalah sakit hati kupikir tidak ada. Bahkan pencuri tidak akan pernah meneriaki dirinya sendiri sebagai pencuri. Dan kebohongan itu kukatakan sambil menyilang jariku ke belakang. Rie tidak melihatnya.
“Ya deh. Tapi jangan kebanyakan ngelamun gitu dong,” balas Rie sedikit cemberut.
Berikutnya matematika. Dua ditambah tiga sama dengan enam. Ada yang salah. Aku tahu. Dua ditambah tiga itu enam. Enam. Enam. Eh, lima! Nah, kan. Patah hati memang menghancurkan mental seseorang. Tepatnya aku. Oh, cepatlah bel istirahat kedua berbunyi.
Dan, bel istirahat kedua pun berbunyi. Saatnya beraksi.
“Mao. Kamu mau ke mana? Kantin yuk. Lapar nih,” ajak Rie tiba-tiba saat aku berdiri.
“Hm, aku udah kenyang kok. Aku harus pergi. Ada sedikit urusan,” jawabku spontan sambil terus memikirkan alasan yang tepat. “Aku harus menemui Bu Siwi. Aku khawatir hasil ulangan kimia kemarin. Aduh, aku takut remidi.”
“Huh. Ya udah. Aku makan sama Windi aja,” balas Rie. “Tanyain nilaiku juga ya. Aku belum belajar juga soalnya.”
“Ya.”
Aku berjalan sendiri menuju ruang kelas Kak Noah. Kelas XII A7. Ruang kelas tepat di samping perpustakaan. Aku sedikit gemetar. ‘Semua akan baik-baik saja,’ batinku menyemangati diri sendiri. Aku mengetuk pintu kelas.
“Eh, Mao. Ada apa? Tumben mampir ke sini,” sapa seorang kakak kelas lalu menghampiriku. Aku mencoba mengingatnya.
“Kak Diaz, Kak Noah mana?” tanyaku sopan.
“Oh. Noah ya? Hm,” Kak Diaz berputar dan melihat sekeliling ruang kelas. “Itu dia. Duduk di belakang. Aku panggilin ya.”
“Ah, iya kak.”
“Hei, Noah! Ada yang nyariin kamu nih!” teriak Kak Diaz lantang.
“Hah? Siapa?” tanya suara di belakang. Aku tahu suara bernada berat ini. Kak Noah. Untung saat istirahat ini, kelas Kak Noah lumayan sepi. Aku tidak bisa membayangkan betapa malunya aku jika kelas di depanku ini ramai penuh dengan teman-teman Kak Diaz dan Kak Noah yang lainnya.
“Mao. Adik kelas,” jawab Kak Diaz.
“Ya. Sebentar.”
Kulihat sekilas Kak Noah berjalan mendekatiku. Dari tatapannya, aku tahu ia pasti bingung tentang siapa aku sebenarnya.
“Oh ya, Mao. Aku mau ke perpustakaan nih. Mumpung belum bel masuk. Aku tinggal dulu ya,” pamit Kak Diaz berjalan pergi meninggalkanku sendiri mematung di depan pintu kelasnya.
“Ya kak. Makasih banyak ya Kak Diaz,” jawabku lirih dengan senyum yang aku tahu sangat kupaksakan. Hatiku berdebar tak keruan. Kak Noah berdiri di depanku.
“Ah. Kamu yang selalu bareng sama Rie itu ya?”
“I-iya kak,” jawabku gugup.
“Ada apa?”
“Oh, ini kak,” kataku sambil menyerahkan amplop surat padanya. Kak Noah sedikit terkejut. Namun sedetik kemudian raut mukanya kembali seperti biasa. Tenang. Terlalu tenang malah.
“Semalam aku tidak sengaja menemukannya saat membaca Novel Maryamah Karpov dari perpustakaan. Aku tahu ini milik kakak dari buku peminjam terakhir novel ini. Aku tahu kalau aku lancang. Maafkan aku kak.”
“Eh. Nggak apa-apa kok. Aku malah senang kamu nemuinnya. Soalnya aku lupa naruhnya di mana. Makasih ya,” kata Kak Noah lalu tersenyum manis.
“Ya. Sama-sama kak,” balasku sambil melangkah pergi.
“Eh, tunggu dulu. Kamu, siapa tadi? Mao ya?”
“Hm, iya kak. Mao Maura.”
“Nama yang bagus.”
“Ng? Makasih kak. Aku pergi dulu.” Aku melangkah kembali ke kelas. Perutku keroncongan pun tak kuhiraukan. Aku sedikit terobati oleh senyumannya yang manis itu. Senyum Kak Noah saat aku mulai berjalan meninggalkannya dan kudengar samar ia berkata, ’ya sama-sama’.
Aku berjalan linglung. Aku bingung. Aku sedih karena Kak Noah tidak melihatku, yang dilihatnya hanya Rie. Tapi aku senang karena dapat melihatnya tersenyum manis. Sungguh aneh tapi nyata. Inilah aku dengan senyum getir terlukis di bibirku dan tatapan nanar lurus ke depan seolah aku dapat melihat menembus tembok. Padahal tidak. Mataku ini masih normal. Tanpa minus ataupun plus dan tentu, tanpa kacamata.
Aku duduk di bangkuku dan mulai membuka Maryamah Karpov lagi. Membaca halaman 400, aku sedikit terkejut. Aku menemukan namaku. Dan Mahar, sejak Maura melepas penutup wajahnya tadi, tak lepas-lepas menatap perempuan paras elok itu. Sayangnya, aku sama sekali tidak cantik. Inilah yang membuatku putus asa.
“Wah, kenyang nih ! Hehe. Kamu?” tanya Rie lalu dengan seenaknya duduk di sampingku membuyarkan lamunanku.
“Nggak lapar kok. Biasa aja.”
“Oh. Gitu ya.”
“Ya. Abis gimana lagi? Kamu aneh deh.”
“Kamu tuh yang aneh. Dari tadi ngelamun terus. Kenapa sih?” tanya Rie.
“Nggak ada,” balasku santai.
“Eh, tahu Kak Noah nggak? Kapten basket itu loh.”
“He-eh. Terus kenapa?”
“Kemarin sore, aku balik lagi ke sekolah soalnya buku catatan biologiku ketinggalan. Mana sepi, kelasnya dikunci lagi. Aku kan belum kenal sama penjaga sekolah kita. Eh malah dibantu Kak Noah.”
“Oh, terus?” tanyaku penasaran.
“Ya awalnya sih aku bingung mau ngambilnya gimana. Terus aku dengar suara bola basket dari lapangan di belakang kelas kita itu. Ya aku ke sana dong.”
“Terus?”
“Kamu tahu nggak? Kak Noah latihan basket di sana. Kak Noah sendirian! Banyangin! Sendirian aja. Mainnya bagus banget lagi. Aku liatin aja sambil berdiri mematung di dinding kelas. Eh, malah dideketin. Aku senang banget dong. Hehe.”
“Oh. Kapan sih kamu nggak senang?” tanyaku spontan. Ups. Aku salah ngomong. Aku terlalu iri padanya.
“Hah? Maksud kamu apa?”
“Ng, nggak kok. Nggak ada. Lanjut aja!”
“Ya gitu. Pas udah selesai masukin bola, Kak Noah nyamperin aku. Dia tanya gini, ’Kenapa Rie?’ Aku bingung dong. Darimana Kak Noah tahu namaku. Terus Kak Noah bilang gini, ’Ah ya. Kenalin, aku Noah temennya Diaz.’ Baru deh aku teringat kakak kelas kita itu. Kak Diaz.”
“Oh. Kak Diaz. Ya. Aku juga ingat.”
“Lha terus aku cerita kalau buku catatanku ketinggalan. Eh, Kak Noah malah dengan senang hati bantu meminjamkan kunci kelas kita pada Pak Sule. Penjaga Sekolah kita itu. Ha! Aku sungguh terkesan. Yang ku tahu, Kak Noah tidak mengenalku. Tapi ternyata aku salah. Baru kusadari, kalau aku selalu terbayang akan senyumannya yang manis itu. Aku menyayanginya. Mao ! Aku me-nyayanginya!”
Deg! Hatiku yang pecah bertambah hancur berantakan bersamaan dengan bel masuk yang berbunyi. Aku total tidak bisa berkonsentrasi lagi. Aku hanya mengangguk saat Pak Eko menegurku melamun di jam Bahasa Inggrisnya. Aku hanya meringis saat Bu Siwi menyindirku karena aku hanya diam saat jam kimianya berlangsung. Aku merasa hampa. Ya. Yang kurasakan hanya hampa.
Aku bahkan sudah tidak bersorak lagi saat mendengar bel pulang berbunyi. Aku berbeda. Aku tidak seperti biasanya.
Aku berjalan malas melewati pagar sekolah. Aku berjalan lelah menuju rumah. Aku terlalu malas untuk menoleh ke kanan-kiri saat akan menyeberang.
Tiba-tiba, aku mendengar suaraku yang nyaring berteriak spontan bersamaan dengan bunyi bel truk yang melaju kencang dari arah samping. Kemudian kurasakan perih di mataku karena yang ku tahu, tubuhku menghantam aspal penuh batu. Lalu semuanya gelap. Hitam pekat.
-Й-
Aku mencoba membuka mata. Namun bagaimanapun juga, setiap kelopak mataku membuka, aku tetap tidak melihat apapun. Semuanya hitam. Semuanya gelap. Aku panik. Aku takut gelap.
“Aarrgghh.........!!” teriakku frustasi.
Yang kutahu sekarang tanganku di-genggam seseorang.
“Mao, tenang sayang. Mama di sini,” kata Mama menenangkanku. “Pa, Papa!! Cepat panggil Dokter Naru! Mao sudah sadar.”
“Apa?! Ya, Ma! Tunggu sebentar. Papa akan memanggil beliau,” jawab Papa dari kejauhan. Kemudian kudengar langkah kaki Papa berlari.
“Mama ada di sini sayang.” Mama menggenggam tanganku lebih erat.
“Ah, Mama! Gelap, Ma! Gelap! Hidupkan lampunya. Kumohon,” pintaku. Kurasakan bulir air mata hangat mengalir di kedua pipiku. Namun di sisi lain, menetes pula air mata Mama di tanganku.
“Sabar ya sayang. Mama ada di sini. Mama ada di samping kamu nak.”
“Mama, Mao mau melihat awan lagi! Mao mau melihat langit biru itu lagi. Melihat pelangi lagi, Ma! Melihat Mama tersenyum. Melihat Papa tersenyum. Mao ingin melihat seperti dulu! Kenapa semuanya gelap?! Mao takut gelap, Ma!!”
“Adik Mao. Adik sabar dulu ya. Adik sedang dalam masa penyembuhan.”
“Apa?! Ini siapa?”
“Saya Dokter Naru. Dokter spesialis mata yang merawat adik.”
“Ya, dok. Tapi kapan saya sembuh?! Saya ingin melihat lagi. Saya takut gelap. Huhuhu... ”
“Tenang sayang. Papa sama Mama akan menemani kamu,” kata Papa lirih.
“Adik yang sabar ya. Adik pasti sembuh,” kudengar lagi suara Dokter Naru. Kemudian kurasakan suntikan menyakitkan di tangan kiriku. Aku kembali tidak sadar.
-Й-
Aku bangun dari ketidaksadaranku. Gelap. Untuk kesekian kalinya aku mencoba membuka kelopak mata tapi tetap memiliki hasil yang sama. Gelap. Aku memang terbaring di tempat tidur. Tapi aku tahu dengan pasti bau yang khas ini. Bau bermacam-macam obat yang menusuk hidung. Rumah sakit.
“Ma, Mama,” panggilku lemah. Tidak ada jawaban. Namun aku belum menyerah.
“Mama...” Aku memanggil dengan suara sedikit keras sambil duduk di atas tempat tidur. Aku meraba-raba. Tidak mendapatkan apapun. Hanya udara hampa.
“Mama. Mama di mana?” Aku bangun dari tempat tidur. Sekali lagi meraba udara. Kosong.
Aku berjalan lurus hingga tanganku mencapai dinding rumah sakit yang dingin. Seperti rumah sakit pada umumnya, tembok dingin di depanku memiliki pegangan besi di sepanjangnya. Memanjang tepat setinggi tanganku dapat meraihnya. Akupun merasa tertolong dengan berjalan berpegangan pada besi itu.
“Papa, Mama ! Kalian di mana?” panggilku serak. Aku menemukan pintu. Aku membukanya. Aku keluar dari ruangan yang menyesakkan itu. Ruangan yang penuh dengan udara kosong tanpa kehadiran manusia. Hanya aku. Hanya aku sendiri.
Aku duduk di bangku yang kupikir tepat di depan ruanganku. Lalu aku diam. Tak bergerak. Sampai kudengar seseorang mengajakku bicara.
“Hai, apa kabar?”
“..... ” Aku diam. Mungkin saja bukan aku yang diajaknya bicara. Mungkin seseorang yang lain. Seseorang yang ada di sekitarku.
“Aku Dei. Kamu siapa? Halo?” tanya suara itu lagi sambil menyentuh tanganku. Hangat.
“Ah, maaf. Aku tidak bisa melihat.”
“Oh. Maaf aku lancang.”
“Tidak apa-apa. Salam kenal, aku Mao.”
“Mao? Nama yang bagus,” kata Dei lembut. Mendengar ini membuatku teringat akan seseorang. Kak Noah. Apa yang sedang dilakukannya? Aku tidak tahu. Aku tidak peduli. Aku tidak mau tahu lagi. Luka di hatiku kembali menganga. Perih.
“Benarkah? Terima kasih,” balasku sambil tersenyum. Senyum yang kupaksakan.
“Kamu sakit? Mau kupanggilkan dokter?” tanya Dei khawatir.
“Tidak, Dei. Aku baik-baik saja,” jawabku bohong.
“Kamu sendirian ya?”
“Sepertinya iya. Mungkin Mama masih pergi sebentar. Dan kupikir, Papa mungkin sedang bekerja saat ini.”
“Wah. Jangan khawatir Mao, kamu nggak sendirian kok. Kan ada aku.”
“Hahaha. Kamu lucu ya, Dei.”
“Masa sih? Hehe. Boleh aku duduk di samping kamu?”
“Boleh kok.”
“Kamu udah lama di sini? Kok aku nggak pernah lihat kamu sebelumnya.”
“Nggak. Aku mungkin baru dua hari di sini. Aku selalu berada di tempat tidur.”
“Oh, gitu ya? Kamu kelas berapa?”
“Kelas sepuluh.”
“Wah adik kelasku dong. Sebulan yang lalu aku masih kelas sebelas. Sekarang mungkin juga masih kelas sebelas. Hehe.”
“Jadi, aku harus panggil kamu kakak ya? Kak Dei?”
“Enggak. Nggak perlu kayak gitu, Mao. Aku masuk kelas akselerasi kok. Jadi umurku masih lima belas.”
“Eh? Sama dong.”
“Emangnya kamu lahir tanggal berapa? Seminggu lagi aku ulang tahun. Tepatnya 1 Desember ”
“Hm. Aku 11 Desember.”
“Wah, aku lebih tua sepuluh hari dong. Jadi, aku emang udah tua kali ya?”
“Mungkin iya!” jawabku antusias. “Bisa kubayangkan kok, Dei. Kalau kamu udah punya keriput. Hehehe,” jawabku asal.
“Apa? Aku ini masih tampan, Mao. Setampan Daniel Radcliffe, kau tahu?”
“Ya. Si Harry Potter itu, kan?”
“Tepat sekali.”
“Hahaha. Jangan bercanda, Dei.”
“Aku tidak berbohong. Periksa denyut nadiku.”
“Kau percaya diri sekali, Dei. Oke, aku percaya kamu.”
“Nah, gitu dong. Hehe.”
Kamipun bercanda tawa. Ya. Kami selalu bertemu seperti ini saat Mama atau Papaku pergi. Dei selalu menemaniku. Tapi, Kak Noah, Kak Diaz, teman-teman sekelasku tidak pernah peduli padaku. Oh, aku bahkan tidak punya teman. Rie tidak sekalipun pernah mengunjungiku. Mereka yang kukenal. Entahlah, aku seolah tidak pernah ada. Hilang dari ingatan mereka.
Lalu saat itupun tiba. Saat dimana semuanya terjadi. Hari ulang tahun Dei sekaligus hari operasi kami. Ya, Dei dan aku menghadapi operasi di hari yang sama. Operasi mata untukku. Tapi aku tidak tahu Dei akan menjalani operasi apa. Aku bahkan tidak tahu Dei sakit apa. Dei tidak pernah mau membahasnya.
“Mao, siap?” suara Dei memanggilku.
“Ya. Aku siap, Dei. Aku tahu. Aku siap untuk melihat lagi. Melihat awan putih di langit yang biru itu lagi.” Aku terdiam untuk saat yang agak lama. “Kau tahu, Dei?”
“Hmm?” gumam Dei.
“Aku benar-benar siap menghadapi semuanya.”
“Ya. Aku juga, Mao. Aku juga.” Kemudian kami berpisah. Akupun kembali tidak sadar.
-Й-
Untuk Mao yang kusayangi,
Aku mohon. Ingat aku, Mao. Ingat aku agar aku tetap hidup walau dalam hati seseorang. Agar aku yakin. Aku pernah ada di dunia ini.
Aku mohon. Saat Mao yang cantik membaca surat ini, ia akan tersenyum. Karena ia dapat melihat lagi.
Aku mohon. Saat Mao yang manis membaca surat ini, ia akan selalu riang, bahkan jika aku sudah tidak ada di sampingnya lagi.
Manusia itu hidup tidak pernah sendiri Mao. Bagaimanapun juga.
Dei.
Aku membaca berulang-ulang barisan kalimat ini. Aku memang sedang berjalan melewati lorong rumahku yang gelap. Namun, aku tetap membacanya. Aku sudah hapal setiap kata yang ditulis Dei dalam selembar kertas yang kini kupegang.
Gelap yang tak berujung. Aku tahu rumahku memang besar dan memiliki berbagai ruang rahasia yang tidak kuketahui. Aku terus berjalan.
Tiba-tiba aku melihat sesuatu. Aku terkejut. Sebentuk cahaya bersinar melayang sejauh lima meter di depanku. Ia memanggilku.
“Mao, kau ingat aku?”
Ya, aku ingat. Tentu saja aku ingat. Suara yang membuatku damai. Suara yang menenangkanku saat aku duduk sendirian di depan ruang di rumah sakit itu. Suara yang selalu terdengar ramah. “Dei!” teriakku sambil berlari ke arahnya.
Dei. Benarkah ini Dei yang selalu menemaniku itu? Aku memeluknya. Hangat. Sehangat tangannya yang kuingat pernah memegangku dulu saat kami pertama bertemu.
“Ya, Mao. Ini aku.”
“Dei? Kau tampan sekali.”
“Hahaha. Aku sudah bilang kan? Aku tidak berbohong.”
“Ya, Dei. Aku percaya kamu,” jawabku lalu mengangguk. “Tapi kamu nggak setampan Daniel Radcliffe tahu! Kamu bohong.”
“Apa? Mao, kuberi tahu ya. Aku tidak pernah berbohong.
“Hah? Kamu itu setampan Justin Bieber! Cobalah sekali-kali lihat dirimu sendiri.”
“Jah, yang penting aku tampan kan? Hehe.”
“Ya, ya sudahlah.”
“Hahaha. Kamu tambah cantik deh.”
“Ng? Aku salah dengar ya? Aku ini jelek tahu. Aku pernah memecahkan kaca saat bercermin.”
“Nggak, Mao. Kamu nggak jelek kok. Kamu itu cantik. Mana ada cewek yang tampan? Nggak ada kan?”
“Hm. Iya sih.”
“Nah, manusia itu dilahirkan jadi cowok sehingga ia tampan. Seperti aku in. Hehehe.” Dei berhenti sejenak. “Lalu ada cewek sehingga ia cantik. Jangan anggap dirimu jelek karena menurutku kamu cantik. Dan akan selalu seperti itu.”
“Makasih Dei.”
“Karena itu aku akan selalu mencintaimu.”
“Aku juga Dei. Aku juga menyayangimu.”
"Ngomong-ngomong, selamat ulang tahun, Mao."
"Kau mengingatnya? Makasih Dei." Aku tersenyum simpul.
Akupun mengikuti Dei. Mengikutinya terbang melayang tinggi hingga aku dapat menyentuh kapas-kapas putih awan yang basah dan dingin. Aku dapat melayang bersama Dei yang selalu menggenggamku erat menuju langit yang biru. Langit yang penuh kedamaian.
Kudengar Dei berbisik di telingaku dengan suaranya yang merdu. “Aku akan selalu bersamamu, Mao. Aku akan selalu menjagamu. Selamanya.”
Aku tidak perduli lagi kalau Mama ataupun Papa menemukan jasadku tergeletak di lorong gelap itu. Aku telah menemukan kebahagiaanku. Karena ada Dei. Karena aku tidak sendiri lagi.
-fin- :)
Labels: PM
A Story: Alone
WRITTEN BY -PM- ON Friday, December 03, 2010 {
4 comments }
Original by me. :) Happy Reading~
SORRY. Indonesia Only
Aku berjalan melewati lorong-lorong gelap. Memang hanya gelap tak berujung yang dapat kulihat. Seingatku, aku tidak dapat ‘melihat’ saat itu. Melihat dengan jelas karena aku terlalu sibuk dengan perasaanku sendiri. Namun kini aku dapat melihatnya. Tersenyum ke arahku. Dan memanggilku dengan suaranya yang merdu.
-Й-
“Ma, aku berangkat dulu ya!” seruku nyaring sambil menutup pintu perlahan.
“Ya, sayang. Hati-hati di jalan,” jawab Mama dari dapur.
Aku berjalan santai melewati jalanan yang sepi. Pukul 6 pagi. Memang jarak rumahku ke sekolah dekat sekali. Cukup dengan sepuluh menit berjalan. Dan berjalan adalah hobiku. Apalagi dengan memandangi matahari yang tersenyum manis dari ufuk timur itu. Membentuk lukisan alam yang indah dipadu dengan langit biru dan beberapa kapas putih awan yang melayang tinggi nun jauh di sana.
Hobiku yang lainnya mungkin adalah menyanyi. Bukan nyanyian yang se-sungguhnya melainkan senandung dalam hati. Aku tidak peduli dengan suaraku yang terlalu nyaring dan tidak cocok untuk menyanyi karena aku hanya menyanyi untuk diriku sendiri. Menyanyi dalam hati. Tentu saja.
Bukan tanpa alasan aku bersenandung riang pagi ini. Bukan senandung dalam hati itu. Senandung yang lain. Senandung berupa nyanyian yang menurutku merdu dengan siulan burung dari dahan-dahan pohon yang rindang. Hanya karena satu hal yang menurutku penting. Aku akan menemuinya. Apapun yang terjadi. Menemui kakak senior itu. Kak Noah.
Dengan satu tarikan nafas, Aku berjalan melewati pintu pagar sekolahku. SMAN 1 Genteng. Cukup mudah untuk berjalan melewati pagar sekolah hingga ke kelas bagi pelajar golongan 'bukan anak populer' sepertiku. Semua tidak mengenalku. Mungkin karena aku selalu sendiri. Dan aku selalu tidak terlihat.
Kesendirian itulah yang kadang menyiksaku. Aku tidak punya teman. Tapi mungkin, Rie satu-satunya temanku. Ia duduk sebangku denganku. Bahkan sejak SMP kami selalu duduk sebangku. Rie jugalah satu-satunya orang yang mau mendengarku bercerita tentang semuanya. Kecuali tentang satu hal. Ia tidak tahu kalau aku menyukai Kak Noah. Dan seperti biasa, ia selalu datang lima menit sebelum bel masuk berbunyi.
“Hah.. hah.. sial..! Nyaris nih pintu gerbang ditutup! Hah... Untung aku kuat lari lagi. Hahaha. Hah.. hah.. Mao ! Hampir aja namaku tercantum di BK!” ujar Rie di sela nafasnya yang terputus-putus.
“Ampun dah. Besok pake alarm yang besar aja, sekalian seperti miliknya Spongebob! Hehe, ” jawabku asal.
“Jah, enggak bakal ada Em !” protes Rie sambil meletakkan tas dan duduk di bangkunya. Ah ya. Rie selalu memanggilku dengan sebutan ini.
“Huh, iya deh,” jawabku tak acuh.
Bel masuk pun berbunyi.
Pelajaran berlalu seperti biasa. Mencatat. Menjawab pertanyaan guru. Maju mengerjakan soal latihan di papan tulis dan ulangan. Aku dengan gembira yang berlebihan segera melonjak dari tempat duduk saat bel istirahat pertama berdering. Akupun bergegas menuju perpustakaan. Tak lupa kubawa juga novel Maryamah Karpov karya Andrea Hirata yang tebal dan penting itu. Bukan novelnya yang penting, tetapi sepucuk surat yang terselip di dalamnya. Dan semalam, aku melihat daftar peminjam terakhir novel itu. Kak Noah.
Sesampainya di perpustakaan, aku meminjam buku daftar anggota perpustakaan dari Bu Siti. Untungnya, beliau dengan senang hati meminjamkannya padaku. Lekas kucari nama Kak Noah. Kak Noah. Oh tidak. Aku bahkan tidak tahu nama lengkapnya. Noah Adisaputra/XI A2/1556, bukan. Yang kutahu, Kak Noah sekarang sudah kelas dua belas. Kucari lagi daftar nama ‘Noah’. Noah Aldebaran/XII A7/1331, yup ketemu.
Aku tidak tahu kelas Kak Noah. Namun, kini aku tahu. Akupun kembali ke kelas dan duduk membaca Maryamah Karpov itu lagi sambil menunggu bel masuk berbunyi. Kurasakan kupu-kupu mengepakkan sayapnya dan menggelitik perutku menciptakan perasaan aneh. Aku bahkan menyukai perasaan ini.
Aku memang penasaran dengan sepucuk surat yang kuanggap milik Kak Noah ini. Bagaimanapun juga, aku berniat membukanya. Toh pikiranku tidak bisa konsentrasi membaca selembar Maryamah Karpov karena setelah itu, aku membaca surat Kak Noah.
Untuk Rie Rahma,
Rie, seperti itukah aku harus memangggilmu? Boleh kan aku memanggilmu dengan sebutan Rahma? Boleh kan? Jawab iya dan mengangguklah. Ah, iya. Aku tidak bisa melihatmu mengangguk. Haha.. Aku ini aneh ya?
Rahma, kau ingat saat MOS dulu? Aku selalu memandangmu. Aku bahkan berfikir untuk mendekatimu tapi aku takut. Aku takut kau akan pergi. Jadi lewat surat ini, aku ingin mengatakan kalau aku menyayangimu apa adanya.
Noah Aldebaran.
Deg! Jadi saat MOS dulu bukan aku yang dilihat Kak Noah. Tapi Rie! Rie yang duduk di sampingku. Rie yang selalu ada di sampingku saat kami makan bersama di kantin atau membaca buku di perpustakaan. Hatiku pecah berkeping-keping. Bagaimana aku bisa menggambarkannya? Seperti perkakas yang jatuh berdentuman di toko kelontong Sinar Harapan saat Ikal patah hati di Laskar Pelangi. Ya, seperti itu. Sungguh menyakitkan. Andai jantungku berhenti ber-detak mungkin sakitnya takkan separah ini.
Jadi seperti inilah sakit hati. Sungguh sepadan dengan jatuh cinta yang melambung tinggi. Sakit hati malah membawaku seperti terjatuh dalam jurang yang dalam tak terkira. Dalam. Dalam sekali. Bahkan seperti ada yang menusuk di dada dan menekan paru-paru hingga sesak. Ingin ku merasakan sakit gigi saja. Setidaknya gigi yang sakit masih dapat diobati. Tapi hati ? Takkan pernah ada obatnya.
Aku yang terlalu bodoh. Aku yang terlalu percaya diri. Aku sungguh malu pada diriku sendiri. Memangnya aku ini siapa? Aku hanya seorang Mao Maura yang tidak punya apa-apa. Aku hanya seorang cewek yang berkulit hitam terbakar matahari yang bahkan sangat kubenci.
Aku benci diriku sendiri. Aku hanya seorang cewek dengan tinggi normal yang tidak dapat menjadi lebih tinggi. Kenapa? Aku ini cewek Asia yang sudah pasti pendek sebagai ciri khas Indonesia daerah pedesaan khususnya. Kekurangan kalsium tingkat tinggi.
Untuk itu aku seringkali ingin merasa egois. Aku ingin dicintai. Tapi oleh siapa? Sampai saat ini, aku bahkan belum pernah punya pacar. Sungguh.
Akupun menutup surat Kak Noah dan memasukkannya kembali ke amplopnya dengan gemetar. Beranikah aku menemuinya setelah aku mengetahui semua ini? Kuharap tidak. Tapi hati kecilku berkata lain. Aku akan tetap menemuinya. Apapun yang terjadi. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri.
Bel masuk pun berdering.
Pelajaran dimulai lagi. Fisika. Rumus GMB. Gerak Melingkar Beraturan. Omega sama dengan dua phi kali frekuensi. Bla.. bla.. bla. Aku benar menyimak Pak Sulton menerangkan tetapi pikiranku melayang jauh hingga kemana-mana. Aku sama sekali tidak bisa berkonsentrasi.
“Em!” panggil Rie samar-samar. Aku tidak begitu mendengarkannya.
“Mao! Sst...!” panggil Rie lagi. Masih dengan berbisik.
“Hm? Apa?” jawabku malas lalu menoleh ke arahnya.
“Kamu sakit ya?” tanya Rie.
“Nggak. Aku nggak apa-apa kok,” jawabku bohong. Orang sakit yang mengaku sakit untuk masalah sakit hati kupikir tidak ada. Bahkan pencuri tidak akan pernah meneriaki dirinya sendiri sebagai pencuri. Dan kebohongan itu kukatakan sambil menyilang jariku ke belakang. Rie tidak melihatnya.
“Ya deh. Tapi jangan kebanyakan ngelamun gitu dong,” balas Rie sedikit cemberut.
Berikutnya matematika. Dua ditambah tiga sama dengan enam. Ada yang salah. Aku tahu. Dua ditambah tiga itu enam. Enam. Enam. Eh, lima! Nah, kan. Patah hati memang menghancurkan mental seseorang. Tepatnya aku. Oh, cepatlah bel istirahat kedua berbunyi.
Dan, bel istirahat kedua pun berbunyi. Saatnya beraksi.
“Mao. Kamu mau ke mana? Kantin yuk. Lapar nih,” ajak Rie tiba-tiba saat aku berdiri.
“Hm, aku udah kenyang kok. Aku harus pergi. Ada sedikit urusan,” jawabku spontan sambil terus memikirkan alasan yang tepat. “Aku harus menemui Bu Siwi. Aku khawatir hasil ulangan kimia kemarin. Aduh, aku takut remidi.”
“Huh. Ya udah. Aku makan sama Windi aja,” balas Rie. “Tanyain nilaiku juga ya. Aku belum belajar juga soalnya.”
“Ya.”
Aku berjalan sendiri menuju ruang kelas Kak Noah. Kelas XII A7. Ruang kelas tepat di samping perpustakaan. Aku sedikit gemetar. ‘Semua akan baik-baik saja,’ batinku menyemangati diri sendiri. Aku mengetuk pintu kelas.
“Eh, Mao. Ada apa? Tumben mampir ke sini,” sapa seorang kakak kelas lalu menghampiriku. Aku mencoba mengingatnya.
“Kak Diaz, Kak Noah mana?” tanyaku sopan.
“Oh. Noah ya? Hm,” Kak Diaz berputar dan melihat sekeliling ruang kelas. “Itu dia. Duduk di belakang. Aku panggilin ya.”
“Ah, iya kak.”
“Hei, Noah! Ada yang nyariin kamu nih!” teriak Kak Diaz lantang.
“Hah? Siapa?” tanya suara di belakang. Aku tahu suara bernada berat ini. Kak Noah. Untung saat istirahat ini, kelas Kak Noah lumayan sepi. Aku tidak bisa membayangkan betapa malunya aku jika kelas di depanku ini ramai penuh dengan teman-teman Kak Diaz dan Kak Noah yang lainnya.
“Mao. Adik kelas,” jawab Kak Diaz.
“Ya. Sebentar.”
Kulihat sekilas Kak Noah berjalan mendekatiku. Dari tatapannya, aku tahu ia pasti bingung tentang siapa aku sebenarnya.
“Oh ya, Mao. Aku mau ke perpustakaan nih. Mumpung belum bel masuk. Aku tinggal dulu ya,” pamit Kak Diaz berjalan pergi meninggalkanku sendiri mematung di depan pintu kelasnya.
“Ya kak. Makasih banyak ya Kak Diaz,” jawabku lirih dengan senyum yang aku tahu sangat kupaksakan. Hatiku berdebar tak keruan. Kak Noah berdiri di depanku.
“Ah. Kamu yang selalu bareng sama Rie itu ya?”
“I-iya kak,” jawabku gugup.
“Ada apa?”
“Oh, ini kak,” kataku sambil menyerahkan amplop surat padanya. Kak Noah sedikit terkejut. Namun sedetik kemudian raut mukanya kembali seperti biasa. Tenang. Terlalu tenang malah.
“Semalam aku tidak sengaja menemukannya saat membaca Novel Maryamah Karpov dari perpustakaan. Aku tahu ini milik kakak dari buku peminjam terakhir novel ini. Aku tahu kalau aku lancang. Maafkan aku kak.”
“Eh. Nggak apa-apa kok. Aku malah senang kamu nemuinnya. Soalnya aku lupa naruhnya di mana. Makasih ya,” kata Kak Noah lalu tersenyum manis.
“Ya. Sama-sama kak,” balasku sambil melangkah pergi.
“Eh, tunggu dulu. Kamu, siapa tadi? Mao ya?”
“Hm, iya kak. Mao Maura.”
“Nama yang bagus.”
“Ng? Makasih kak. Aku pergi dulu.” Aku melangkah kembali ke kelas. Perutku keroncongan pun tak kuhiraukan. Aku sedikit terobati oleh senyumannya yang manis itu. Senyum Kak Noah saat aku mulai berjalan meninggalkannya dan kudengar samar ia berkata, ’ya sama-sama’.
Aku berjalan linglung. Aku bingung. Aku sedih karena Kak Noah tidak melihatku, yang dilihatnya hanya Rie. Tapi aku senang karena dapat melihatnya tersenyum manis. Sungguh aneh tapi nyata. Inilah aku dengan senyum getir terlukis di bibirku dan tatapan nanar lurus ke depan seolah aku dapat melihat menembus tembok. Padahal tidak. Mataku ini masih normal. Tanpa minus ataupun plus dan tentu, tanpa kacamata.
Aku duduk di bangkuku dan mulai membuka Maryamah Karpov lagi. Membaca halaman 400, aku sedikit terkejut. Aku menemukan namaku. Dan Mahar, sejak Maura melepas penutup wajahnya tadi, tak lepas-lepas menatap perempuan paras elok itu. Sayangnya, aku sama sekali tidak cantik. Inilah yang membuatku putus asa.
“Wah, kenyang nih ! Hehe. Kamu?” tanya Rie lalu dengan seenaknya duduk di sampingku membuyarkan lamunanku.
“Nggak lapar kok. Biasa aja.”
“Oh. Gitu ya.”
“Ya. Abis gimana lagi? Kamu aneh deh.”
“Kamu tuh yang aneh. Dari tadi ngelamun terus. Kenapa sih?” tanya Rie.
“Nggak ada,” balasku santai.
“Eh, tahu Kak Noah nggak? Kapten basket itu loh.”
“He-eh. Terus kenapa?”
“Kemarin sore, aku balik lagi ke sekolah soalnya buku catatan biologiku ketinggalan. Mana sepi, kelasnya dikunci lagi. Aku kan belum kenal sama penjaga sekolah kita. Eh malah dibantu Kak Noah.”
“Oh, terus?” tanyaku penasaran.
“Ya awalnya sih aku bingung mau ngambilnya gimana. Terus aku dengar suara bola basket dari lapangan di belakang kelas kita itu. Ya aku ke sana dong.”
“Terus?”
“Kamu tahu nggak? Kak Noah latihan basket di sana. Kak Noah sendirian! Banyangin! Sendirian aja. Mainnya bagus banget lagi. Aku liatin aja sambil berdiri mematung di dinding kelas. Eh, malah dideketin. Aku senang banget dong. Hehe.”
“Oh. Kapan sih kamu nggak senang?” tanyaku spontan. Ups. Aku salah ngomong. Aku terlalu iri padanya.
“Hah? Maksud kamu apa?”
“Ng, nggak kok. Nggak ada. Lanjut aja!”
“Ya gitu. Pas udah selesai masukin bola, Kak Noah nyamperin aku. Dia tanya gini, ’Kenapa Rie?’ Aku bingung dong. Darimana Kak Noah tahu namaku. Terus Kak Noah bilang gini, ’Ah ya. Kenalin, aku Noah temennya Diaz.’ Baru deh aku teringat kakak kelas kita itu. Kak Diaz.”
“Oh. Kak Diaz. Ya. Aku juga ingat.”
“Lha terus aku cerita kalau buku catatanku ketinggalan. Eh, Kak Noah malah dengan senang hati bantu meminjamkan kunci kelas kita pada Pak Sule. Penjaga Sekolah kita itu. Ha! Aku sungguh terkesan. Yang ku tahu, Kak Noah tidak mengenalku. Tapi ternyata aku salah. Baru kusadari, kalau aku selalu terbayang akan senyumannya yang manis itu. Aku menyayanginya. Mao ! Aku me-nyayanginya!”
Deg! Hatiku yang pecah bertambah hancur berantakan bersamaan dengan bel masuk yang berbunyi. Aku total tidak bisa berkonsentrasi lagi. Aku hanya mengangguk saat Pak Eko menegurku melamun di jam Bahasa Inggrisnya. Aku hanya meringis saat Bu Siwi menyindirku karena aku hanya diam saat jam kimianya berlangsung. Aku merasa hampa. Ya. Yang kurasakan hanya hampa.
Aku bahkan sudah tidak bersorak lagi saat mendengar bel pulang berbunyi. Aku berbeda. Aku tidak seperti biasanya.
Aku berjalan malas melewati pagar sekolah. Aku berjalan lelah menuju rumah. Aku terlalu malas untuk menoleh ke kanan-kiri saat akan menyeberang.
Tiba-tiba, aku mendengar suaraku yang nyaring berteriak spontan bersamaan dengan bunyi bel truk yang melaju kencang dari arah samping. Kemudian kurasakan perih di mataku karena yang ku tahu, tubuhku menghantam aspal penuh batu. Lalu semuanya gelap. Hitam pekat.
-Й-
Aku mencoba membuka mata. Namun bagaimanapun juga, setiap kelopak mataku membuka, aku tetap tidak melihat apapun. Semuanya hitam. Semuanya gelap. Aku panik. Aku takut gelap.
“Aarrgghh.........!!” teriakku frustasi.
Yang kutahu sekarang tanganku di-genggam seseorang.
“Mao, tenang sayang. Mama di sini,” kata Mama menenangkanku. “Pa, Papa!! Cepat panggil Dokter Naru! Mao sudah sadar.”
“Apa?! Ya, Ma! Tunggu sebentar. Papa akan memanggil beliau,” jawab Papa dari kejauhan. Kemudian kudengar langkah kaki Papa berlari.
“Mama ada di sini sayang.” Mama menggenggam tanganku lebih erat.
“Ah, Mama! Gelap, Ma! Gelap! Hidupkan lampunya. Kumohon,” pintaku. Kurasakan bulir air mata hangat mengalir di kedua pipiku. Namun di sisi lain, menetes pula air mata Mama di tanganku.
“Sabar ya sayang. Mama ada di sini. Mama ada di samping kamu nak.”
“Mama, Mao mau melihat awan lagi! Mao mau melihat langit biru itu lagi. Melihat pelangi lagi, Ma! Melihat Mama tersenyum. Melihat Papa tersenyum. Mao ingin melihat seperti dulu! Kenapa semuanya gelap?! Mao takut gelap, Ma!!”
“Adik Mao. Adik sabar dulu ya. Adik sedang dalam masa penyembuhan.”
“Apa?! Ini siapa?”
“Saya Dokter Naru. Dokter spesialis mata yang merawat adik.”
“Ya, dok. Tapi kapan saya sembuh?! Saya ingin melihat lagi. Saya takut gelap. Huhuhu... ”
“Tenang sayang. Papa sama Mama akan menemani kamu,” kata Papa lirih.
“Adik yang sabar ya. Adik pasti sembuh,” kudengar lagi suara Dokter Naru. Kemudian kurasakan suntikan menyakitkan di tangan kiriku. Aku kembali tidak sadar.
-Й-
Aku bangun dari ketidaksadaranku. Gelap. Untuk kesekian kalinya aku mencoba membuka kelopak mata tapi tetap memiliki hasil yang sama. Gelap. Aku memang terbaring di tempat tidur. Tapi aku tahu dengan pasti bau yang khas ini. Bau bermacam-macam obat yang menusuk hidung. Rumah sakit.
“Ma, Mama,” panggilku lemah. Tidak ada jawaban. Namun aku belum menyerah.
“Mama...” Aku memanggil dengan suara sedikit keras sambil duduk di atas tempat tidur. Aku meraba-raba. Tidak mendapatkan apapun. Hanya udara hampa.
“Mama. Mama di mana?” Aku bangun dari tempat tidur. Sekali lagi meraba udara. Kosong.
Aku berjalan lurus hingga tanganku mencapai dinding rumah sakit yang dingin. Seperti rumah sakit pada umumnya, tembok dingin di depanku memiliki pegangan besi di sepanjangnya. Memanjang tepat setinggi tanganku dapat meraihnya. Akupun merasa tertolong dengan berjalan berpegangan pada besi itu.
“Papa, Mama ! Kalian di mana?” panggilku serak. Aku menemukan pintu. Aku membukanya. Aku keluar dari ruangan yang menyesakkan itu. Ruangan yang penuh dengan udara kosong tanpa kehadiran manusia. Hanya aku. Hanya aku sendiri.
Aku duduk di bangku yang kupikir tepat di depan ruanganku. Lalu aku diam. Tak bergerak. Sampai kudengar seseorang mengajakku bicara.
“Hai, apa kabar?”
“..... ” Aku diam. Mungkin saja bukan aku yang diajaknya bicara. Mungkin seseorang yang lain. Seseorang yang ada di sekitarku.
“Aku Dei. Kamu siapa? Halo?” tanya suara itu lagi sambil menyentuh tanganku. Hangat.
“Ah, maaf. Aku tidak bisa melihat.”
“Oh. Maaf aku lancang.”
“Tidak apa-apa. Salam kenal, aku Mao.”
“Mao? Nama yang bagus,” kata Dei lembut. Mendengar ini membuatku teringat akan seseorang. Kak Noah. Apa yang sedang dilakukannya? Aku tidak tahu. Aku tidak peduli. Aku tidak mau tahu lagi. Luka di hatiku kembali menganga. Perih.
“Benarkah? Terima kasih,” balasku sambil tersenyum. Senyum yang kupaksakan.
“Kamu sakit? Mau kupanggilkan dokter?” tanya Dei khawatir.
“Tidak, Dei. Aku baik-baik saja,” jawabku bohong.
“Kamu sendirian ya?”
“Sepertinya iya. Mungkin Mama masih pergi sebentar. Dan kupikir, Papa mungkin sedang bekerja saat ini.”
“Wah. Jangan khawatir Mao, kamu nggak sendirian kok. Kan ada aku.”
“Hahaha. Kamu lucu ya, Dei.”
“Masa sih? Hehe. Boleh aku duduk di samping kamu?”
“Boleh kok.”
“Kamu udah lama di sini? Kok aku nggak pernah lihat kamu sebelumnya.”
“Nggak. Aku mungkin baru dua hari di sini. Aku selalu berada di tempat tidur.”
“Oh, gitu ya? Kamu kelas berapa?”
“Kelas sepuluh.”
“Wah adik kelasku dong. Sebulan yang lalu aku masih kelas sebelas. Sekarang mungkin juga masih kelas sebelas. Hehe.”
“Jadi, aku harus panggil kamu kakak ya? Kak Dei?”
“Enggak. Nggak perlu kayak gitu, Mao. Aku masuk kelas akselerasi kok. Jadi umurku masih lima belas.”
“Eh? Sama dong.”
“Emangnya kamu lahir tanggal berapa? Seminggu lagi aku ulang tahun. Tepatnya 1 Desember ”
“Hm. Aku 11 Desember.”
“Wah, aku lebih tua sepuluh hari dong. Jadi, aku emang udah tua kali ya?”
“Mungkin iya!” jawabku antusias. “Bisa kubayangkan kok, Dei. Kalau kamu udah punya keriput. Hehehe,” jawabku asal.
“Apa? Aku ini masih tampan, Mao. Setampan Daniel Radcliffe, kau tahu?”
“Ya. Si Harry Potter itu, kan?”
“Tepat sekali.”
“Hahaha. Jangan bercanda, Dei.”
“Aku tidak berbohong. Periksa denyut nadiku.”
“Kau percaya diri sekali, Dei. Oke, aku percaya kamu.”
“Nah, gitu dong. Hehe.”
Kamipun bercanda tawa. Ya. Kami selalu bertemu seperti ini saat Mama atau Papaku pergi. Dei selalu menemaniku. Tapi, Kak Noah, Kak Diaz, teman-teman sekelasku tidak pernah peduli padaku. Oh, aku bahkan tidak punya teman. Rie tidak sekalipun pernah mengunjungiku. Mereka yang kukenal. Entahlah, aku seolah tidak pernah ada. Hilang dari ingatan mereka.
Lalu saat itupun tiba. Saat dimana semuanya terjadi. Hari ulang tahun Dei sekaligus hari operasi kami. Ya, Dei dan aku menghadapi operasi di hari yang sama. Operasi mata untukku. Tapi aku tidak tahu Dei akan menjalani operasi apa. Aku bahkan tidak tahu Dei sakit apa. Dei tidak pernah mau membahasnya.
“Mao, siap?” suara Dei memanggilku.
“Ya. Aku siap, Dei. Aku tahu. Aku siap untuk melihat lagi. Melihat awan putih di langit yang biru itu lagi.” Aku terdiam untuk saat yang agak lama. “Kau tahu, Dei?”
“Hmm?” gumam Dei.
“Aku benar-benar siap menghadapi semuanya.”
“Ya. Aku juga, Mao. Aku juga.” Kemudian kami berpisah. Akupun kembali tidak sadar.
-Й-
Untuk Mao yang kusayangi,
Aku mohon. Ingat aku, Mao. Ingat aku agar aku tetap hidup walau dalam hati seseorang. Agar aku yakin. Aku pernah ada di dunia ini.
Aku mohon. Saat Mao yang cantik membaca surat ini, ia akan tersenyum. Karena ia dapat melihat lagi.
Aku mohon. Saat Mao yang manis membaca surat ini, ia akan selalu riang, bahkan jika aku sudah tidak ada di sampingnya lagi.
Manusia itu hidup tidak pernah sendiri Mao. Bagaimanapun juga.
Dei.
Aku membaca berulang-ulang barisan kalimat ini. Aku memang sedang berjalan melewati lorong rumahku yang gelap. Namun, aku tetap membacanya. Aku sudah hapal setiap kata yang ditulis Dei dalam selembar kertas yang kini kupegang.
Gelap yang tak berujung. Aku tahu rumahku memang besar dan memiliki berbagai ruang rahasia yang tidak kuketahui. Aku terus berjalan.
Tiba-tiba aku melihat sesuatu. Aku terkejut. Sebentuk cahaya bersinar melayang sejauh lima meter di depanku. Ia memanggilku.
“Mao, kau ingat aku?”
Ya, aku ingat. Tentu saja aku ingat. Suara yang membuatku damai. Suara yang menenangkanku saat aku duduk sendirian di depan ruang di rumah sakit itu. Suara yang selalu terdengar ramah. “Dei!” teriakku sambil berlari ke arahnya.
Dei. Benarkah ini Dei yang selalu menemaniku itu? Aku memeluknya. Hangat. Sehangat tangannya yang kuingat pernah memegangku dulu saat kami pertama bertemu.
“Ya, Mao. Ini aku.”
“Dei? Kau tampan sekali.”
“Hahaha. Aku sudah bilang kan? Aku tidak berbohong.”
“Ya, Dei. Aku percaya kamu,” jawabku lalu mengangguk. “Tapi kamu nggak setampan Daniel Radcliffe tahu! Kamu bohong.”
“Apa? Mao, kuberi tahu ya. Aku tidak pernah berbohong.
“Hah? Kamu itu setampan Justin Bieber! Cobalah sekali-kali lihat dirimu sendiri.”
“Jah, yang penting aku tampan kan? Hehe.”
“Ya, ya sudahlah.”
“Hahaha. Kamu tambah cantik deh.”
“Ng? Aku salah dengar ya? Aku ini jelek tahu. Aku pernah memecahkan kaca saat bercermin.”
“Nggak, Mao. Kamu nggak jelek kok. Kamu itu cantik. Mana ada cewek yang tampan? Nggak ada kan?”
“Hm. Iya sih.”
“Nah, manusia itu dilahirkan jadi cowok sehingga ia tampan. Seperti aku in. Hehehe.” Dei berhenti sejenak. “Lalu ada cewek sehingga ia cantik. Jangan anggap dirimu jelek karena menurutku kamu cantik. Dan akan selalu seperti itu.”
“Makasih Dei.”
“Karena itu aku akan selalu mencintaimu.”
“Aku juga Dei. Aku juga menyayangimu.”
"Ngomong-ngomong, selamat ulang tahun, Mao."
"Kau mengingatnya? Makasih Dei." Aku tersenyum simpul.
Akupun mengikuti Dei. Mengikutinya terbang melayang tinggi hingga aku dapat menyentuh kapas-kapas putih awan yang basah dan dingin. Aku dapat melayang bersama Dei yang selalu menggenggamku erat menuju langit yang biru. Langit yang penuh kedamaian.
Kudengar Dei berbisik di telingaku dengan suaranya yang merdu. “Aku akan selalu bersamamu, Mao. Aku akan selalu menjagamu. Selamanya.”
Aku tidak perduli lagi kalau Mama ataupun Papa menemukan jasadku tergeletak di lorong gelap itu. Aku telah menemukan kebahagiaanku. Karena ada Dei. Karena aku tidak sendiri lagi.
-fin- :)
Labels: PM